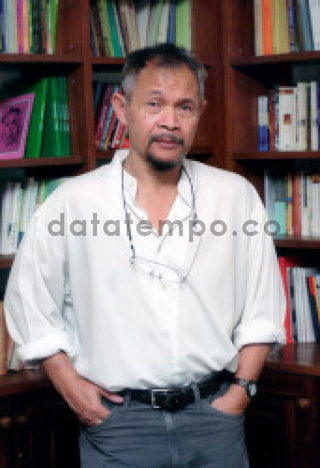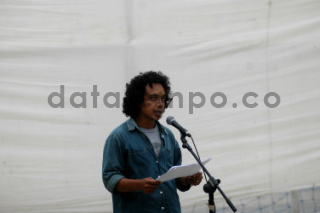Siti Nurbaya 1991
Edisi: 10/21 / Tanggal : 1991-05-04 / Halaman : 41 / Rubrik : KAL / Penulis :
Siti Nurbaya 1991
Siti Nurbaya: Roman, Wanita, dan Sejarah TAUFIK ABDULLAH
Siti Nurbaya pada Dekade 1990 JULIA I. SURYAKUSUMA
Potret Perempuan dalam Novel Indonesia LEILA S. CHUDORI
PENGASUH: Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Bambang Bujono, Isma Sawitri, Budiman S. Hartoyo, Leila S. Chudori, Yudhi Soerjoatmodjo, Edi R.M.
SUDAH lama kehadiran majalah kebudayaan terdepak ke pinggir rel, di negeri ini. Sejak Budaja Djaja mengembuskan napas terakhir, pada akhir tahun 70-an tinggallah majalah Horison -- lebih banyak memuat karya sastra -- yang terasa bertambah pucat dan tepos. Serta majalah Basis di Yogya yang dalam kesepiannya masih berusaha hidup terus dengan gagah.
Lembaran-lembaran kebudayaan di berbagai media, yang terjepit di antara kobaran berita dan kejayaan iklan, mencoba melarikan tongkat estafet. Tetapi pemikiran-pemikiran budaya (serta karya sastra) masih tetap tak memiliki beranda bermain yang lega. Barangkali itu pula yang menyebabkan ada dampak seperti kemacetan pemikiran budaya dan pencarian-pencarian dalam karya seni. Kesenian pun seakan-akan tak penting, tak berguna, dan tanpa daya.
TEMPO, sejak penerbitan ini, secara berkala, empat bulan sekali akan hadir dengan Kalam. Lembaran yang memberikan tempat pada pemikiran-pemikiran budaya serta karya seni-sastra. Semoga oase kecil ini dapat merangsang penciptaan karya unggul dan pemikiran budaya yang brilyan di masa datang. Pada penampilan pertama ini kami ketengahkan Julia I. Suryakusuma, Taufik Abdullah, dan Leila S. Chudori, yang membicarakan wanita dalam karya sastra Indonesia.
Siti Nurbaya: Roman, Wanita, dan Sejarah
TAUFIK ABDULLAH
BARANGKALI "Siti Nurbaya" tak perlu lagi diperkenalkan. Entah sejak kapan, nama ini seakan-akan telah merupakan lambang wanita modern yang teraniaya oleh kekuasaan adat. Dalam anggapan umum kekuasaan adat ini dipersonifikasikan oleh Datuk Meringgih. Tak ada tokoh fiktif sastra Indonesia modern yang bisa menandingi kemampuan personifikasi nilai dari kedua nama ini. Bahkan Syamsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya yang berhasil membalas kematian kekasihnya, setelah lebih dulu berpidato dan berpetuah, sambil berduel, tidak bisa menyamai mereka. Juga tidak oleh "Hanafi", meskipun sebenarnya ia lebih memikat. Ia, si Malin Kundang, dalam konteks hubungan kolonial tergelincir pada kedurhakaan, akibat Salah Asuhan. Kemampuan personifikasi nilai juga tak tertandingi oleh "Tono", "Tini" dan "Yah" yang bergumul dalam pembebasan diri dari belenggu, demi hari depan yang tanpa kepastian.
Tetapi benarkah Marah Rusli, pengarang roman Siti Nurbaya, dengan sengaja membuat dunia rekaannya sebagai suatu forum perbenturan cita-cita baru, yang baik dan maju, melawan kekuatan lama, yang kolot dan terkebelakang? Ia tidak mengatakannya. Seandainya ia pernah mengatakannya kemudian, pada kesempatan lain, tiada kepastian yang bisa dipegang bahwa itu adalah hal yang sesungguhnya. Bukan karena ia berbohong. Masalahnya ialah yang ditinggalkannya kepada kita tak lebih dari sebuah dunia simbol yang dibentuk dalam teks. Dan sekali teks itu menampakkan diri, ia -- teks itu -- mempunyai kebebasan untuk mengadakan dialog langsung dengan pembacanya. Maka, pembacalah yang akan memberi makna kepada teks itu.
Suatu tirani telah terjadi, memang. Kehadiran teks serta-merta memutuskan hubungan langsung dan timbal balik antara pengarang teks, atau lebih tepat pemula proses discourse dan kita, sang pembaca. Karena itu, teks itulah yang sesungguhnya harus dihadapi. Keterangan si pengarang (di luar teks) tak lebih dari bahan tambahan untuk mendapatkan suasana yang akrab ketika proses dialog, antara kita dan teks, sedang terjadi.
"Kekejaman" teks yang memisahkan kita dengan pengarangnya sebenarnya telah tertebus oleh kehadiran teks itu. Bukankah teks itu pula yang menyebabkan proses dialog, yang dimulai pengarang, menjadi abadi dan menyebar? Tetapi inilah masalahnya, bagaimana kita akan bisa menangkap pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan teks lewat kisah yang diceritakan itu. Apakah kisah hanyalah sekadar kisah, sebagai pelipur lara, perentang hari menjelang petang? Ataukah suatu berita pikiran yang memantulkan keprihatinan kultural, politik, atau apa saja? Andaikan teks ini hanyalah pelipur lara, bukankah kelaraan hanya bisa terlipur bila yang melipurnya melemparkan lambang-lambang yang serasi? Dan keserasian lambang itu sifatnya his toris dan kultural. Jadi, ditentukan oleh struktur waktu dan tempat. Kalau begitu, bagaimana?
Sebaiknya kita beranjak dari sebuah patokan awal bahwa makna teks sastra akan lebih mungkin dipahami jika kita menempatkannya kembali ke dalam konteks masyarakat dan zaman yang menghasilkannya. Dengan kata lain, kita usahakan agar teks itu berdialog dengan konteksnya yang paling intim. Siapa tahu, kesediaan kita untuk menjadikan teks itu sebagai pasangan discourse dari konteks penciptaannya akan memungkinkan kita menangkap makna "sesuatu tentang sesuatu" yang ingin disampaikan oleh kisah yang diceritakan. Dan siapa tahu pula, "yang sesuatu itu" dalam konteks sekarang adalah sesungguhnya bayangan keprihatinan kultural yang berlanjut. Siapa tahu! Hanya saja, kemungkinan-kemungkinan hipotetis ini bisa pula mengatakan hal yang lain tentang teks Apa yang secara eksplisit dikatakan barangkali tidak tidak lebih penting dari apa yang tidak dikatakan.
Subjudul dari karya sastra ini ialah: "Kasih tak Sampai". Jadi ini adalah kisah kasih dua remaja yang patah di tengah jalan. Memang, suatu tema yang abadi, dulu dan kini, di sana dan di sini. Tetapi Siti Nurbaya adalah kisah kasih pada zaman tertentu dan di tempat tertentu pula -- di Kota Padang, di peradilan abad ini. Kekuatan roman ini memang terletak pada usaha untuk menjadikan tema abadi ini secara lokal dan temporal bermakna. Kelemahan strukturnya juga kelihatan nyata pada aspek ini.
Roman ini seakan-akan terbagi atas dua bagian yang tak organik -- bagian pertama adalah kisah dua remaja, yang teraniaya, sedangkan bagian kedua (pada halaman yang terpencar-pencar) adalah "berita pikiran" tentang berbagai masalah kemasyarakatan. Bagian pertama adalah suatu kisah melodrama -- kisah manusia yang terimpit oleh kelemahannya -- sedangkan bagian kedua adalah usaha untuk berdialog dengan masyarakat pembaca, sambil memberi komentar terhadap dunia rekaan yang diciptakan lewat plot cerita.
CINTA kasih remaja bukanlah tema yang asing dalam tradisi sastra Indonesia, atau lebih khusus, Minangkabau. Akhir tragis dari kisah ini terjadi karena sesungguhnya "cinta remaja" itu adalah pemberontakan terhadap kewajaran kultural. Kegagalan mereka adalah kemenangan tata kosmos yang wajar dan telah teruji. Hasrat individu pun harus kalah, demi keutuhan tata kosmos sosial dan tradisi. Tetapi kegagalan cinta Nurbaya dan Samsulbahri bukan karena "pemberontakan" yang tak sah. Kasih mereka "tak sampai" karena intervensi kekuatan luar, yang dipersonifikasikan oleh Datuk Meringgih, yang ternyata terlalu kuat dan terlalu jahat untuk bisa diatasi.
Lebih dari itu, struktur realitas sosial seakan-akan memberi kemungkinan bagi "kekuatan jahat" dari luar ini untuk berbuat tidak semena-mena. Kekuasaan hukum pemerintah dapat dimanipulasi oleh Datuk Meringgih untuk mengancam Baginda Suleiman, yang telah dianiayanya, dan untuk menjerat kembali Siti Nurbaya, yang telah berkumpul dengan kekasihnya, di Betawi. Etik kemegahan bangsawan, yang selalu dipompakan oleh Putri Rubiah kepada adiknya, Sutan Mahmud, ayah Syamsul Bahri, akhirnya mendorong Sutan Mahmud untuk mengusir anak tunggal kesayanganrya. Maka, situasi melodramatis tak terelakkan lagi. Sutan Mahmud bukan "Hamlet", tetapi pilihan yang dibuatnya untuk mengatasi dilema etis yang dihadapinya, antara cinta pada anak dan rasa kehormatan yang ternodai, berakhir tragis bagi keluarganya.
Kedua remaja ini adalah anak kota yang terpelajar dan berasal dari "kalangan atas" masyarakat pribumi. Ayah Nurbaya adalah seorang saudagar besar yang jujur dan arif, "meskipun bukan seorang yang berasal tinggi" (hlm. 14). Tetapi perilaku dan kekayaannya telah menjadikan ia dan anaknya, Siti Nurbaya yang cantik, diterima dan diperlakukan sebagai "bangsawan hati". Karena tak ada sedikit pun keterangan tentang sanak saudara Baginda Suleiman, bisa diperkirakan bahwa ia adalah pendatang ke Kota Padang dan kawin dengan keluarga yang cukup terkemuka. Setelah ia meninggal, Nurbaya tinggal bersama sepupunya (tampaknya dari pihak ibu), Siti Alimah. Sedangkan Samsul Bahri adalah anak bangsawan, pejabat tinggi di Kota Padang, tetapi ibunya (sebagaimana diejek oleh Putri Rubiah -- hlm. 22) adalah "orang kebanyakan". Karena itulah Samsulbahri "hanya marah", bukan seseorang yang berhak memakai gelar "sutan", seperti ayahnya. Nurbaya (dan juga Alimah, sepupunya, yang impulsif), adalah "sitti" (bukan "pnri" atau "puti", seperti Putri Rubiah).
Jadi, teks ini berkisah tentang golongan sosial pengarangnya sendiri -- - mereka yang bergelar "marah" dan "sitti", yang meski bangga dengan "bangsanya yang tinggi", toh cukup sadar akan proses erosi kebangsawanan yang sedang terjadi (hlm. 196).
Tetapi siapakah Datuk Meringgih? Ia seorang kaya, teramat kaya, tetapi "tiadalah ia berbangsa tinggi" dan Marah Rusli pun menghabiskan hampir lima halaman teks (83-88) untuk menceritakan kejelekan tokoh antagonis ini. Yang jelas adalah bahwa kekayaannya yang melimpah ruah itu datangnya "misterius" sehingga berbagai dugaan orang tentang asal-usul kekayaan orang yang mulanya hanyalah pedagang ikan asin di pasar Jawa ini.
Meskipun memakai gelar "datuk", ia sama sekali bukanlah penghulu adat, "melainkan panggilan saja baginya" (83). Tetapi mengapa ia harus mendapat panggilan dan senang dipanggil "datuk"? Menurut tradisi adat Kota Padang, hanya delapan orang yang berhak bergelar "datuk". Jadi, pasti Datuk Meringgih bukan anggota komunitas adat Padang. Kalau begitu, ia dipanggil "datuk" karena ia adalah seorang upstart yang datang dari wilayah Minangkabau, yang mempunyai banyak "datuk" (penghulu adat), yaitu Luhak nan Tigo di pedalaman (Padangsche Bovenlanden, kata orang Belanda).
Dari susunan para "aktor" ini barangkali tidak terlalu sukar untuk memperkirakan bahwa kesemuanya berada dalam proses peralihan. Putri Rubiah dan adiknya Sutan Hamzah, yang sibuk kawin, bukanlah orang-orang jahat. Hanya saja, mereka buta terhadap perubahan yang sedang terjadi di sekitar mereka. Maka, mereka pun tak lebih dari karikatur, yang lucu, dan sekaligus menjengkelkan.
Baginda Suleiman (seperti juga Ahmad Maulana, ayah Alimah) adalah "orang baru" yang arif mereka bergabung ke dalam local establishment kawin dan mengikatkan diri pada nilai dasar dari komunitas baru yang dimasukinya. Datuk Meringgih dengan serakah dan jahat memanipulasi situasi yang mengalir ini hanya untuk memuaskan nafsu serakahnya. Ia membawa kebinasaan kepada dunia yang tertib -- sebuah dunia epos, bukannya novel, jika klasifikasi Lucas boleh dipakai -- yang sadar sedang memasuki gerbang "kemajuan". Inilah dunia yang ditandai oleh pendidikan tinggi, ekonomi yang maju, pejabat yang bertanggung jawab, dan romantic love yang direstui. Dan, tentu, warga yang patuh pada pemerintah (kolonial), yang memperkenalkan pajak, demi perbaikan masyarakat.
Jika demikian "Zaman Siti Nurbaya" bukanlah zaman kekolotan yang menyesakkan, tetapi zaman perubahan yang mendebarkan. Tetapi, mengapa Nurbaya membiarkan dirinya menjadi korban keserakahan Datuk Meringgih, yang telah menjerat ayahnya ke dalam utang? Pengorbanannya tidak saja menghancurkan masa depan yang telah diimpikannya dengan Samsulbahri, tetapi juga menimbulkan penyesalan mendalam dari ayahnya -- rasa penyesalan yang mempercepat kematian. Sebuah melodrama yang murni, memang. Namun, karena ini pula, tampak-tampaknya roman ini memakai judul Siti Nurbaya.
Meskipun dalam masyarakat matrilineal kedudukan laki-laki selalu kritis, wanitalah yang secara simbolik dipakai sebagai "indikator sosial". Unsur simbolik ini pulalah yang berperan sebagai alat integratif literer antara aspek fiksi, yang bercorak melodrama (Kasih tak Sampal, dan "berita pikiran" yang ingin disampaikan. Jadi, keutuhan fiksi harus dicari bukan pada perkembangan logika dunia rekaan ini, tetapi pada judul simbolik yang berbunyi keras dalam konteks sosial-historis yang menghasilkannya.
Apa pun coraknya, novel atau karya imajinatif lain tak bisa diperlakukan sebagai "monumen", tonggak peringatan peristiwa di masa lalu. Ia hanyalah "dokumen", kesaksian tentang suasana hati dan pikiran masyarakat dari zaman penciptaannya. Dan sebagai dokumen, Siti Nubaya memang sangat kaya. Lewat dialog yang berpanjang-panjang, tokoh-tokohnya menyampaikan berita pikiran tentang kekolotan yang merugikan di kalangan bangsawan (hlm. 18-27 56-64) kearifan hidup dalam zaman perubahan ( 131-143) corak perkawinan yang ideal dan semestinya (144-149) kejelekan poligami (195-201) masalah hubungan perempuan dan laki-laki (201-210), dan sebagainya.
Dengan menyampaikan "berita pikiran" itu, roman ini seakan ingin merekam secara utuh masalah-masalah yang merupakan fokus perdebatan intens selama dua tiga dasawarsa di peralihan abad ini di Kota Padang -- kota…
Keywords: Sastra, Kebudayaan, Taufik Abdullah, Leila S Chudori, Julia I Suryakusuma, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Bambang Bujono, Isma Sawitri, Budiman S. Hartoyo, Yudhi Soerjoatmodjo, Edi R.M,
Artikel Majalah Text Lainnya
MUSIK, TEATER, DAN POLITIK BUDAYA KOLONIAL PADA MASA RAFFLES DI JAWA 1811-1816
1993-05-01Franki raden, peneliti musik, mengetengahkan perkembangan seni, musik, teater, budaya politik kolonial di kota-kota besar…
FILM DI INDONESIA: ANTARA PERTUMBUHAN DAN KECEMASAN
1993-05-01Tanggapan garin nugroho, sutradara film, tentang gejala perfilman indonesia selama 20 tahun terakhir. ia tak…
DUA ZAMAN, DUA POLITIK KEBUDAYAAN: PENGANTAR UNTUK DUA TULISAN
1993-05-01Dua tulisan, masing-masing membahas soal pelbagai peristiwa seni di kota-kota di jawa pada awal abad…