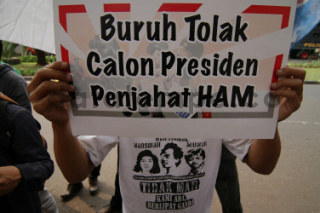Dunia Tidak Hitam Putih
Edisi: 17/19 / Tanggal : 1989-06-24 / Halaman : 51 / Rubrik : MEM / Penulis :
Roeslan Abdulgani, lahir di Plapitan, Surabaya, 24 November 1914, pendidikan His, mulo, hBs. Ia menganggap dunia ini tidak hitam putih tapi berwarna, yang penting orang harus bisa menyesuaikan diri dengan warna-warni itu. Di awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama, ia menduduki posisi-posisi penting. Di zaman Orde Baru posisinya tetap kuat sebagai Dubes RI di PBB (1967-1971), ketua tim penasehat presiden mengenai pelaksanaan P4 (1978-sekarang). Belakangan, ia rajin menulis buku, dan artikel-artikel di mass media. Penuturan sebagaian perjalanan hidupnya ini sengaja kami mintakan lewat reporter kami, Priyono B. Soembogo.
SAYA dilahirkan di Plampitan, salah satu kampung di Kota Surabaya, di dekat Kali Mas, kelanjutan dari Kali Brantas. Saya punya tiga saudara kandung. Kakak saya laki-laki sudah meninggal. Adik saya perempuan masih ada di Surabaya, sudah kawin. Bapak saya punya istri dua. Ibu saya istri kedua. Dengan istri pertama punya tiga anak juga. Tetapi, tentu saja ibu saya dan ibu tiri saya hidup di rumah terpisah.
Kami dididik dengan keras. Bapak mengajarkan kami hidup gemi -- hemat. Meskipun Bapak punya mobil, kalau ke sekolah, kami tidak boleh menggunakannya. Sementara Ibu menyuruh kami selalu eling -- ingat -- pada Tuhan. Bapak meninggal tahun 1929, ketika saya masih di MULO. Sejak itu Ibu yang membiayai sekolah saya. Untung, Bapak mewariskan perusahaan dan sebagainya, sehingga Ibu tetap dapat membiayai saya.
Kalau saya ingat kembali, saya ini produk dari pertemuan dua keadaan: keadaan kampung dan keadaan kota. Kampung di Surabaya, bukan berarti 'kampungan' seperti orang 'gedongan' di sini katakan. Kampung itu suatu masyarakat dinamis, masyarakat di mana ada cerminan daripada seluruh kota Surabaya.
Nah, Surabaya adalah nomor satu kota pedagang. Kedua, adalah kota di mana agama Islam sangat kuat. Ada Sunan Ngampel, ada Masjid Ngampel, ada pesantren-pesantren yang kuat, dan macam-macam. Ketiga, Kota Surabaya adalah kota kaum buruh. Banyak bengkel-bengkel. Malahan di zaman Belanda "Marine". Di sana ada semangat nasionalisme dan semangat keislaman. Itu semua memberi corak tertentu pada Surabaya. Dan kemudian, Kota Surabaya memiliki banyak kerajinan tangan. Jadi, banyak orang yang hidup bebas, yang tidak hidup dari birokrasi. Birokrasi memang ada, tetapi tidak sebegitu menonjol seperti di Batavia.
Tapi jangan dikira Surabaya tidak mempunyai nilai intelektual. Di sana ada sekolah kedokteran yang nomor dua setelah Stovia di Batavia. Di Surabaya ada HBS. Sekolah untuk anak-anak pribumi cuma sedikit. Masa kecil saya tidak bisa saya lepaskan dari kondisi itu. Sebab, itulah yang membentuk pribadi saya.
Kebetulan bapak saya, Haji Abdulgani, adalah orang pedagang yang pandangan hidupnya pragmatis, profesional. Dia tergolong pedagang yang cukupan. Sejajar dengan pedagang-pedagang Cina waktu itu. Bapak saya berdagang berbagai macam dagangan: beras, gula, dan lain-lain. Bapak punya telepon, barang yang waktu itu jarang dimiliki orang. Orang yang punya telepon waktu itu tergolong besar. Di samping itu dia punya 10 mobil yang disewakan sebagai taksi. Lalu, punya rumah-rumah yang disewakan. Kalau ndak salah, 20--30 rumah. Zaman sekarang bisa disebut real estate.
Namun begitu, Bapak saya ikut Syarekat Dagang Islam. Bapak memang tidak ikut dalam politik, tetapi dia ikut memberikan dana bagi gerakan Pak H.O.S. Tjokroaminoto. Rumah Pak Tjokro di seberang rumah kami. Di rumah Pak Tjokro itu juga ada Bung Karno, yang indekos di sana.
Tahun 1926 ada pemogokan-pemogokan. Tahun 1925 Syarekat Islam yang dipimpin Pak Tjokro sudah besar. Ketika Bapak masih hidup, ada pemogokan-pemogokan yang dikerahkan oleh SI pada 1925-1926. Saya masih kecil. Antara SI dan PKI ada kompetisi: Jadi, tidak benar cuma PKI yang melawan kolonialisme. Syarekat Islam juga. Pak Tjokro ditangkap, dimasukkan penjara, dan sebagainya.
Bapak juga merasakan hal itu. Beliau memang tidak ikut berpolitik, tapi memberikan dana. Saya sering diajak ikut melihat pemogokan. Misalnya ke Pasar Keling -- rumah Dinas Kereta Api, namanya dulu SS. Mereka ikut mogok malam-malam, hujan-hujan, lantas diusir oleh polisi. Bapak mengantar saya untuk melihat. "Coba lihat itu, mebel-mebel dikeluarkan dari rumah," kata Bapak. Orang-orang Cina, orang-orang Arab, datang untuk membeli mebelnya. Umur saya waktu itu 16 tahun, masih di HIS kelas 6, begitu. "Itulah kejamnya penjajahan Lodo," kata Bapak. Dan saya sudah tertarik pada pergerakan-pergerakan macam itu.
Bapak juga bercerita tentang K.H. Achmad Dahlan -- pendiri Muhammadiyah -- yang sering datang ke Plampitan, bertemu dengan Tjokroaminoto. Ada juga Nahdlatul Ulama. Selain itu, Perang Dunia I baru saja selesai. Harga gula naik, dan sebagainya. Kota Surabaya sebagai kota dagang jadi bandar yang ramai. Dengan begitu Surabaya menjadi kancah penggodokan berbagai macam orang. Ada ulama, buruh, Belanda, Cina, Arab, dan sebagainya.
Di tengah situasi macam itulah, saya dilahirkan dan hidup. Jadi jangan melihat saya sebagai individu. Tetapi sebagai produk zaman. Ibu saya selalu berkata, "Kita mimpi kapan kita merdeka, kapan Londo itu pergi".
Saya punya mbah, namanya Mbah Kasiran. Saya, Ibu, dan Bapak sering pergi ke sana. Kalau Bapak dan Ibu bicara soal orang-orang yang ditangkapi Belanda, Mbah berkata, "Ojo kuatir (jangan khawatir), Joyoboyo sudah mengatakan, nanti akan datang Bangsa Jago Kate (Dai Nippon) kemari. Nanti sesudah itu Bongso Jowo akan merdeka. Tapi wutah getih -- banjir darah." Ibu saya, Sitti Nurat, seorang guru ngaji. Punya murid kira-kira 50-an. Karena dulu rumah kami cukup besar, cukup untuk menampung murid-murid ngaji, perempuan dan laki-laki. Saya kalau sore harus ikut ngaji. Pagi sekolah. Saya hidup di dua dunia. Kalau pagi Sekolah Dasar, sore mengaji. Di SD saya belajar bahasa Belanda, bahasa Jawa juga -- Paromo Sastro Jowo, yang saya harus kenal. Sepulang sekolah, sorenya saya langsung ikut ngaji. Ya, Jus Amma, Yassin. Ibu minta saya harus bisa baca Surah Yassin. Ndak perlu ngerti. Tentu dimulai dengan menghafal surah Albaqaroh. Cara mengajinya bersama-sama, dengan teman-teman lain. Masing-masing memegang Al-qur'an, sementara Ibu menuntun. Itu berlangsung sampai saya masuk HBS.
Saya disekolahkan di HIS, sekolah dasar yang terletak di Sulung. Selesai tahun 1928. Lulus dari HIS saya disekolahkan ke MULO di Ketabang sampai tahun 1932. Di Surabaya hanya ada dua MULO. Satu di Ketabang satu di Praban. Lulusan Praban misalnya Widjojo Nitisastro, dan istri saya. Kemudian saya pergi ke HBS Surabaya. HBS ini SMA khusus untuk orang Belanda. Tidak ada SMA untuk pribumi. Semestinya saya harus pergi ke Malang. Tetapi saya mengikuti ujian di HBS Surabaya. Padahal bukan untuk pribumi. Saya masuk, saya ditantang ujian bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, goneometri, aljabar, dan lain-lain. Lulus saya. Masuk!
Waktu itu yang berani ujian dari MULO Ketabang hanya empat. Dua orang Cina, satu orang Belanda, satu saya. Belandanya gagal, satu Cina gagal. Swie Ho, yang kemudian jadi pelukis hebat dan sekarang sudah meninggal, tes sama-sama saya. Tujuh ratus murid (700) HBS, 70% di antaranya Belanda totok, 15% orang Indo, 10% Cina. Nah, orang Indonesia cuma 5%. Kira-kira cuma 30 gelintir anak Indonesia. Antara lain Mukarto -- kelak Menteri Luar Negeri -- Sudjatmoko, Murdiyanto. Keduanya adik kelas saya.
Di HBS ini saya baru mengenal masyarakat Belanda. Guru-gurunya lain dengan di MULO. Di MULO anggak-anggak -- galak, sombong, keras. Itu karena muridnya banyak inlander. Di HBS, sinyo-sinyo dan noni-noni hidup dengan bebas. Saya lebur dalam dunia Barat. Sekali lagi, saya hidup dalam dua dunia: dunia modern dan dunia Islam. Tetapi sinyo-sinyo dan guru-guru Belanda itu tidak membedakan pergaulan dengan kalangan pribumi. Di sini saya diajarkan berbagai mata pelajaran. Yang paling saya senangi adalah pelajaran sejarah. Tapi yang mengenai Indonesia seperti sejarah Diponegoro hampir tidak ada. Semua sejarah Eropa. Ada Revolusi Prancis, sejarah revolusi Amerika, sejarah pergolakan di Eropa tahun 1948, imperialisme di Eropa, Terusan Suez di bledak tahun 1870 dan sebagainya. Saya sampai hafal.
Setelah lulus dari HBS tahun 1935, saya terlempar dalam perjuangan. Tahun 30-an, sebelum 1935, Kota Surabaya masih bergolak. Tahun 1932-1932 ada krisis ekonomi di dunia. Saya masih di HBS. Saya belajar ekonomi juga. Karena ada krisis Belanda mengadakan onslag -- pengurangan tenaga-tenaga pegawai. Bayaran dipotong. Opsir-opsir cuma kena 10%. Kemudian yang rendahan kena 30%. Akibatnya, pergolakan semakin meningkat. Di Marine Surabaya, ada yang namanya Kapal VII. Mereka mengadakan pemogokan dan ditangkapi. Sementara ada kapal yang berlayar ke Aceh. Mendengar adanya penangkapan di Surabaya, mereka berontak. Teman saya, Aleks kebetulan menjadi Marine. Dia yang bercerita pada saya. Marine-marine pribumi yang ada di kapal menuju Aceh menangkap kapten kapal -- orang Belanda. Peristiwa ini mengagetkan dunia. "Bukan main orang-orang Indonesia itu." Pak Sungkono ikut di dalamnya. Mereka berlayar kembali ke Surabaya, menuntut supaya kawan-kawannya dilepaskan. Tetapi kemudian bom oleh kapal udara di Bengkulu. Menyerah.
Di HBS Surabaya, ini menjadi pembicaraan. Guru saya, Direktur HBS masuk kelas saya, kira-kira jam 12.00. Saya waktu itu berada di kelas mekanika. "Kamu dengar bahwa pemberontakan sudah dihancurkan. Bom sudah dijatuhkan." Ketika guru itu keluar, salah seorang teman perempuan berteriak sambil tepuk tangan, "Horeee.....!" Lha... guru saya yang lain, yang kebetulan masih di kelas, marah, "Kenapa kamu tepuk tangan. Apa kamu tidak tahu mengapa mereka berontak. Mereka berontak karena melawan ketidakadilan ...." Jadi, di kalangan Belanda sendiri ada perbedaan pendapat, ada yang tidak menyetujui kebijaksanaan Belanda.
Nah, itu yang membawa saya ke suatu pemikiran, bahwa perjuangan kemerdekaan tidak harus ditujukan kepada orang-orang Belanda, tetapi kepada sistemnya. Ini pengaruh HBS kepada saya. Ketika tahun 1933 pemimpin surat kabar Suara Umum, Pak Tjindarboemi ditangkap, Bung Karno dibuang ke Digul, saya masih kelas IV HBS. Di tengah situasi macam itulah masa muda saya berlangsung. Sementara Filipina dijanjikan kemerdekaan. Saya belajar jua soal itu. Di HBS pula saya belajar…
Keywords: -
Artikel Majalah Text Lainnya
Kisah Seputar Petisi 50
1994-02-05Memoar ali sadikin. ia bercerita panjang mengenai petisi 50 dan sisi-sisi kehidupannya
KIAI HAJI ALAWY MUHAMMAD: TAK MUDAH MELUPAKAN KASUS NIPAH
1994-05-28Kh alawy muhammad, 66, tokoh ulama yang menjadi mediator antara pemerintah dan rakyat ketika terjadi…
Anak Agung Made Djelantik: Dokter yang Giat Mengurusi Seni
1994-04-09Memoar anak agung made djelantik, perumus konsep dasar seni lukis bali. ia pernah menggelar festival…